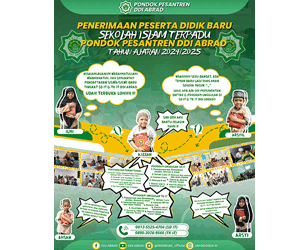Prof. Dr. H. Muh. Suaib Tahir, Lc. MA.
Komitmen Internasional dalam Mencabut Akar Islamofobia Pada tanggal 15 Maret,
Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara resmi menetapkan hari tersebut sebagai Hari Internasional untuk Memerangi Islamofobia.
Keputusan ini dipicu oleh tragedi penembakan di dua masjid di Christchurch, Selandia Baru, yang dilakukan oleh seorang pria bersenjata pada tahun 2019.
Akibat penembakan brutal ini, sebanyak 51 orang meninggal dunia dan 40 lainnya mengalami luka-luka.
Peristiwa tersebut menggugah perhatian dunia terhadap meningkatnya Islamofobia, yang telah menjadi kenyataan yang berkembang di berbagai belahan dunia, seperti yang diungkapkan oleh Utusan Pakistan untuk PBB, Munir Akram.
Islamofobia, sebagai bentuk diskriminasi dan kebencian terhadap umat Muslim, telah menjadi masalah global yang terus berkembang dalam beberapa dekade terakhir.
Sebagai bentuk rasisme baru, Islamofobia sering kali ditandai dengan xenofobia, stereotip negatif, serta profil yang merugikan umat Islam.
Pernyataan ini juga menegaskan bahwa terorisme tidak seharusnya dikaitkan dengan agama, bangsa, atau kelompok etnis manapun.
Terlepas dari latar belakang sosial dan politik, terorisme adalah tindakan individu yang tidak dapat diasosiasikan dengan identitas agama atau etnis tertentu.
Adopsi resolusi PBB ini dilakukan melalui konsensus 193 negara anggota dan disponsori oleh 55 negara mayoritas Muslim.
Fokus utama dari resolusi tersebut adalah perlindungan terhadap hak kebebasan beragama dan berkeyakinan.
Poin penting yang ditekankan dalam resolusi ini adalah penghormatan terhadap simbol dan praktik agama, serta pembatasan terhadap pidato kebencian dan diskriminasi sistematis yang menargetkan umat Islam.
Ketegasan ini menjadi sangat penting karena sering kali sikap intoleran dimulai dari ujaran kebencian yang diperkuat oleh tokoh-tokoh agama atau pemimpin masyarakat di berbagai forum publik, seperti masjid, gereja, dan tempat pertemuan lainnya.
Bagi dunia Islam, keputusan ini merupakan langkah maju yang signifikan.
Di Indonesia, berbagai kebijakan telah diterapkan untuk mendukung misi PBB dalam memerangi Islamofobia.
Salah satunya adalah upaya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam mengategorikan penceramah-penceramah radikal yang dapat memicu paham ekstremisme dan intoleransi.
Jika melihat sejarah, fenomena Islamofobia mulai mencuat pasca tragedi serangan terorisme 11 September 2001 di Amerika Serikat.
Setelah peristiwa tersebut, gelombang kampanye global melawan terorisme menggambarkan komunitas Islam sebagai salah satu kelompok yang terlibat dalam aksi terorisme.
Komunitas Muslim sering kali dipandang sebagai penyebab utama ketegangan sosial dan terorisme.
Di Amerika Serikat, daftar pendatang yang dicurigai sebagai teroris pertama kali dikeluarkan pada 1 Oktober 2002, menyusul serangan 11 September.
Tidak hanya itu, fenomena Islamofobia juga merebak di negara-negara seperti Australia, Inggris, bahkan Indonesia.
Di Indonesia sendiri, ketegangan sosial pasca ledakan bom Bali 2002 menyebabkan penyebaran ketakutan terhadap umat Islam.
Penangkapan sejumlah tokoh Islam yang dianggap terkait dengan serangan terorisme, seperti Amrozi, Ali Imron, Imam Samudra, serta tokoh lainnya, semakin memperburuk persepsi negatif terhadap komunitas Muslim.
Fenomena ini juga menyebabkan stigma terhadap individu yang memelihara jenggot, mengenakan jubah, bercadar, atau bahkan hanya memiliki tanda fisik seperti jidat hitam.
Meski Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk Muslim, fenomena Islamofobia tetap muncul dalam bentuk-bentuk yang lebih halus.
Sebagai contoh, seorang pengusaha kontrakan mungkin merasa khawatir apabila calon penyewa merupakan individu yang mengenakan atribut keagamaan seperti jenggot tebal dan pakaian tertentu.
Kekhawatiran tersebut, meskipun tampak tidak rasional, sesungguhnya merupakan manifestasi dari Islamofobia yang mengakar dalam kesadaran sosial yang dipengaruhi oleh stereotip dan stigmatisasi terhadap umat Islam.
Islamofobia tidak hanya merupakan bentuk prasangka sosial, tetapi juga berpotensi mengarah pada konflik sosial yang lebih luas.
Untuk mencegah hal ini, perlu adanya langkah-langkah konkret yang diambil untuk memperkuat integrasi sosial dan menghormati keragaman identitas.
Salah satu langkah yang efektif adalah dengan mendorong hidup dalam lingkungan yang heterogen, yang memungkinkan masyarakat untuk saling memahami dan menerima perbedaan.
Keterbukaan dalam pandangan dan kemampuan untuk menerima keberadaan identitas lain menjadi kunci utama dalam menciptakan masyarakat yang harmonis dan inklusif.
Sebagai penutup, upaya internasional yang diprakarsai oleh PBB, bersama dengan kebijakan yang ada di tingkat nasional, memegang peranan penting dalam mencegah dan mengurangi Islamofobia.
Pendidikan yang berfokus pada toleransi, penghargaan terhadap keberagaman, dan pembatasan ujaran kebencian adalah langkah-langkah yang harus terus diperjuangkan untuk memastikan terciptanya masyarakat yang adil, damai, dan penuh rasa hormat terhadap hak asasi manusia.